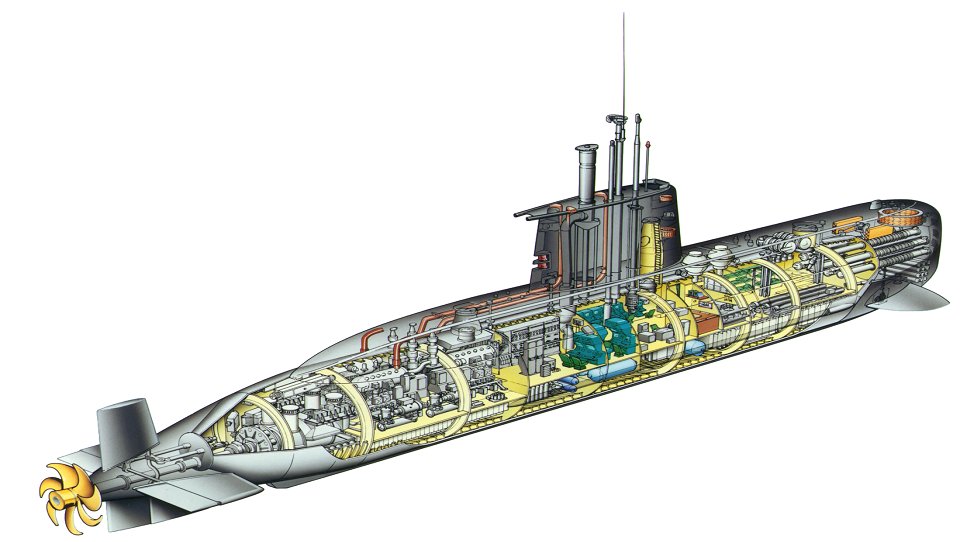September,
tahun 1945. Para pemuda Indonesia sibuk melucuti persenjataan Jepang.
Ibu Umiyah Dayino, 75 tahun, masih ingat sebuah pemandangan. Soeharto,
eks tentara Peta, sering datang ke bilangan Pathook di Yogya. Sebuah
kawasan yang kini terkenal sebagai pusat oleh-oleh bakpia ini, sekitar
50 tahun silam, menjadi sarang berkumpul pemuda-pemuda bawah tanah yang
disebut Kelompok Pathook. Para pemuda itu berkumpul, berdiskusi, berbagi
informasi, merakit senjata, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh
partai. Penggerak-penggerak utama “geng” ini adalah Dayino, Koesomo
Soendjojo, dan Denyoto. Semuanya kini sudah almarhum. Umiyah, yang
tinggal di Ngabean, Yogya, adalah janda dari Dayino. “Dulu, rumah ini
memang menjadi rumah kedua markas pemuda Pathook. Markas utama ada di
rumah Koesomo Soendjojo, di Kampung Pathook,” katanya kepada TEMPO suatu
sore.
Di situlah Soeharto sering mendengar
orang berdiskusi. Memang tak sampai setiap hari, tapi ia bisa saja
mampir dua kali seminggu. Ia tiba setiap pukul delapan malam dan dan
bertahan sampai pukul tiga pagi. Itu semua dilakukan untuk “belajar
politik” kepada Dayitno dan Soendjojo, yang dekat dengan para politisi
sosialis. Adalah Marsoedi, seorang eks tentara Peta, yang memperkenalkan
Soeharto kepada kelompok Pathook. “Pemuda Pathook itu seperti pemuda
Menteng 31 Jakarta. Semua berkumpul di situ, apakah itu PKI atau yang
lain,” tutur Marsoedi, mengenang. Ibrahim, 76 tahun, mantan anggota
Pathook, masih ingat betul bahwa yang sering meladeni makanan atau
minuman untuk Soeharto adalah seorang bernama Munir. Ia adalah Ketua
Serikat Buruh. “Munir kemudian dijatuh hukuman mati oleh Soeharto,
padahal mereka pernah sama-sama di Pathook,” kata Ibrahim. Jika wartawan
menyempatkan diri melacak masa lalu Soeharto di Yogyakarta dan
menemukan kembali aktivis-aktivis Kelompok Pathook dulu itu ada
alasannya.

Sebuah buku berjudul Suharto: A Political Biography
karya R.E. Elson, yang baru saja meluncur dalam jumlah terbatas dan
berharga jual Rp 400 ribu, menyinggung tentang Kelompok Pathook ini.
Boleh disebut di situlah proses pembentukan pemikiran pertama Soeharto.
Atau, bisa dikatakan bahwa Pathook adalah sebuah potret kecil bagaimana
cara dan gaya Soeharto berkawan. Di Pathook, ia tidak larut dalam
pergaulan. Ia mengambil jarak. “Ia bukan anggota,” tutur Ibrahim.
Soeharto lebih banyak diam, tapi agaknya ia secara saksama mengamati
kecenderungan karakter dan sikap orang, sehingga ketika tiba suatu
“masa” ia dihadapkan pada sikap memilih mana kawan, mana lawan, ia telah
siap. Ia bahkan tega mengorbankan sahabatnya sendiri. Munir, yang punya
nama lengkap Mohammad Munir, dieksekusi pada Mei tahun 1985.

Marsudi,
orang yang membukakan cakrawala politik Soeharto, yang kemudian menjadi
perwira intel Soeharto, juga dijebloskan ke penjara selama lima tahun
di zaman Orde Baru. Tudingannya? Anggota Partai Komunis Indonesia. Buku
ini adalah sebuah hasil penelitian yang disusun secara komprehensif dan
hati-hati. Ada beberapa hal yang tetap menjadi pertanyaan: misalnya,
sosok misterius Syam Kamaruzaman, yang sesungguhnya adalah anggota
Kelompok Pathook.
Banyak spekulasi mengatakan, kelak
kemudian hari ia menjadi agen ganda dan merupakan kunci utama Peristiwa
G30S. Sayang, Elson tidak memberi ruang untuk mengeksplorasi misteri
Syam. Ada hal lain yang menarik yang sekilas disentuh Elson, yakni soal
penyelundupan Soeharto akhir tahun 1940-an. Ibu Umiyah, misalnya,
mendengar sebuah versi cerita bahwa, ketika Soeharto memimpin Brigade X
(Wehtkreise III) di Yogyakarta, ia sudah terlibat penyelundupan.
Menggunakan bahan-bahan dari WTIR (Wekelijks Territoriaal Inlichtingen
Rapport) dan NEFIS (Netherland Forces Intelligence Service), Elson
membenarkan dugaan itu. Sayangnya, pemaparannya hanya sekilas. Elson
juga menuturkan periode kepanglimaan Soeharto di Semarang tahun
1950-1959 secara selintas. Pada Juli 1957, saat menjadi Panglima Jawa
Tengah di Semarang, Soeharto mendirikan YPTE (Yayasan Pembangunan
Teritorium Empat).
Mereka mendapatkan modal awal sebesar Rp
419,352 dari pajak kopra dan sumbangan Persatuan Pabrik Rokok Kudus.
Tahun itu juga, Soejono Hoemardani, staf Soeharto, bekerja sama dengan
YPTE mendirikan NV Garam di Salatiga, yang bergerak di bidang
transportasi. YPTE mendapatkan sepuluh persen dari keuntungan. Masih
pada tahun yang sama, Soejono membeli separuh saham PT Dwi Bakti.
Separuh saham lainnya diambil oleh anak angkat Gatot Subroto, yaitu
Mohammad Bob Hassan, dan pengusaha Sukaca. Pada akhir tahun 1957, luar
biasa, modal YPTE langsung mencapai Rp 18 juta. Pada Agustus 1958, YPTE
mendirikan NV Pusat Pembelian Hasil Bumi, perusahaan jual-beli produksi
pertanian.
Pada tahun 1959, kekayaan YPTE melonjak
menjadi Rp 35 jutaan, sehingga YPTE bisa meminjamkan uang sebesar Rp 1
juta rupiah untuk mengembangkan industri kecil di Jawa Tengah. Agustus
1959, YPTE melangkah lebih jauh lagi: menanamkan investasi sebesar Rp 15
juta untuk membeli Pabrik Gula Pakis. Untuk mengatasi kekurangan stok
pangan di Jawa Tengah, Soeharto membuat kebijakan mengadakan barter gula
dengan beras dari Thailand dan Singapura. Maka, diutuslah agen-agen
YPTE bernama Bob Hasan dan Soejono Hoemardani untuk membuat koordinasi
tukar-menukar ilegal antara Jawa Tengah dan Singapura.

Soal
barter inilah yang membawa Soeharto ke hadapan tim pemeriksa Angkatan
Darat dengan tuduhan korupsi. Pada April 1957 di Jakarta, diresahkan
oleh kabar merebaknya korupsi di lingkungan tentara, A.H. Nasution
meng-instruksikan membuat tim investigasi korupsi. Pada 18 Juli 1959,
sebuah tim inspeksi dari Jakarta dipimpin Brigadir Jenderal Sungkono
tiba di Semarang. Aspek-aspek finansial YPTE diperiksa oleh tim yang
diketuai Letnan Kolonel Sumantri. Pada 13 Oktober 1958, Soengkono
mengeluarkan pernyataan pers di Semarang tentang kegiatan YPTE.
Keuntungan yayasan ini digunakan untuk membeli pompa air, traktor, pupuk
para petani di Jawa Tengah, dan untuk membantu para pensiunan ABRI dan
kebutuhan sehari-hari keluarga serdadu, misalnya membantu bila ada
kematian atau pernikahan atau membeli kebutuhan sehari-hari. Akhirnya,
tim tersebut menyatakan bahwa kasus barter ilegal Soeharto “dapat
dimaafkan” lantaran itu dilakukan untuk kesejahteraan petani dan
prajurit.
Posisi Elson sendiri tampak sependapat
dengan “keputusan resmi”. Ia menyangsikan bahwa segala uang itu masuk ke
kantong pribadi Soeharto, lantaran dari risetnya ia mendapat fakta
bahwa kehidupan Soeharto di Semarang sederhana . “As far as I am
aware, Suharto himself was not directly involved in such maters, and
there is no evidence that connects him directly to a share in the
profits of these business, ” (Sepanjang yang saya ketahui, Soeharto
tidak terlibat secara langsung dalam kasus itu, dan tak ada fakta yang
mendukung bahwa dia mendapatkan bagian keuntungan dari bisnis ini-Red.),
demikian ditulis Elson. Elson juga menampik anggapan umum bahwa
hubungan bisnis di bawah tangan antara Soeharto dan Liem Sioe Liong
terjalin di Semarang karena-menurut Elson-pada saat itu fokus bisnis
Liem berganti.
Oktober 1956, Liem mendirikan NV Bank
Asia, yang kelak akan menjadi Bank Central Asia (BCA). Tahun 1957, Liem
telah meninggalkan Kudus dan pindah ke Jakarta. Hubungan erat Soeharto
dan Liem-menurut Elson-baru ketika di Jakarta, di awal Orde Baru. Yang
menjadi soal, dengan kesimpulan seperti itu adakah Elson telah
mewawancarai beberapa saksi hidup saat itu? Wartawan TEMPO menemui Mayor
Jenderal (Purnawirawan) Moehono, yang pada waktu itu menjabat sebagai
Jaksa Agung Muda yang diutus Nasution untuk mendampingi tim kecil
Ibrahim untuk memeriksa Soeharto.
“Jauh sebelum membentuk Yayasan
Teritorial Empat, Soeharto sudah melakukan korupsi, yaitu penjualan
mobil-mobil tua, sejumlah mobil yang usianya belum mencapai lima tahun
ikut dilegonya,” tutur Muhono. Dalam daftar pustaka, misalnya, Elson
menggunakan referensi buku Letnan Jenderal Purnawirawan Mochammad
Jassin, mantan Panglima Komando Daerah Militer Brawijaya 1967-1970: Saya
Tidak Pernah Minta Ampun pada Soeharto.
Entah apakah Elson mewawancarai langsung
Jassin atau tidak. Sebab, dalam wawancaranya dengan media pada tahun
1998, Jassin mengatakan: “Tiga tahun yang lalu saya tanya ke Pak Nas
sewaktu dia mengawinkan cucunya, ‘Pak Nas, katanya Soeharto itu pernah
jadi penyelundup.’ Dia bilang, ‘Iya bukan hanya teh, ada cengkih, besi
tua, tekstil. Menurut Jassin, sebenarnya Soeharto sudah mau dipecat olek
Pak Nas tapi diselamatkan oleh Gatot Soebroto.’
Menurut Muhono, yang pertama kali
melaporkan penyelundupan ini adalah Pranoto Reksosamudra. Itulah
sebabnya Soeharto sangat dongkol kepada Pranoto, yang dikenalnya di
Pathook itu. Ketika di Semarang, ternyata Pranoto menjadi rival politik
Soeharto. Pranoto inilah yang oleh Bung Karno ditunjuk sebagai caretaker
keamanan pasca-G30S. Tapi, kemudian, Pranoto ditahan oleh Soeharto
selama 15 tahun (dari 16 Februari 1966 sampai 16 Februari 1981). Kepada
TEMPO, Umiyah, istri Dayino, menyatakan bagaimana ia ingat saat Pranoto
keluar dari penjara. Ketika itu suaminya, Dayino, menemui Pranoto.
Kedua sahabat ini berangkulan dan Pranoto
berpesan kepada Dayino: “No, kowe ojo melu-melu sing kuoso iki, mergo
sing kuoso iki iblis (Kamu jangan ikut-ikutan yang berkuasa, karena yang
berkuasa ini iblis).” Bagian penting lain yang menarik tapi terasa tak
memuaskan dahaga pembacanya adalah bab G30S-PKI. Elson tampak bersikap
ekstrahati-hati. Ia tidak ingin terjebak dalam teori konspirasi. Ia sama
sekali tidak menyentuh kontroversi keterlibatan CIA di balik G30S-PKI
atau bahwa Soeharto semacam soldier of fortune yang menjual negara.
Bagaimanapun, sikap hati-hati Elson ini
memiliki sisi positif karena ia mampu menunjukkan kritik terhadap Kol.
Latief. Berdasar bahan-bahan wawancara surat kabar, buku, dan pleidoi
Latief, ia menunjukkan beberapa bagian yang tidak konsisten dalam
pernyataan Kolonel Latief. Misalnya, pengakuan Latief bahwa semenjak di
Brigade X ia menjadi anak buah Soeharto bertentangan dengan pengakuannya
yang lain.
Kesimpulan Elson, sebetulnya baik Latief
maupun Untung sama sekali tidak akrab dengan Soeharto. Bahwa fakta
Soeharto pernah menghadiri perkawinan Untung adalah hal yang
dilebih-lebihkan. Elson berpendapat Soeharto tidak terlibat dalam
peristiwa itu. Tapi dia menangguk untung. Bagi Elson, Soeharto adalah
sosok yang sulit diketahui isi hatinya. Di tengah misterinya, Elson
menganggap kekuatan utama Soeharto adalah kemampuannya membuat kalkulasi
politik.
Salah satu prinsip Soeharto: ia tak akan
bertindak sebelum sampai ada tanda jelas. Ia sabar, tahan, menunggu
momen tepat, meskipun dalam rentang itu korban nyawa berjatuhan.
Contohnya adalah pada waktu malam pembunuhan jenderal itu. Mendengar
laporan Latief bahwa ada penculikan jenderal, ia tidak bertindak
apa-apa. Mungkin ia melihat sebuah kesempatan bagi dia sendiri untuk
maju. Demikianlah taktik politik Soeharto.
Menurut analisis Elson, Soeharto juga tak
suka pada seorang pesaing atau rival. Banyak pengamat menganggap,
sesungguhnya dalam praktek politik sehari-hari Soeharto tak ada orang
dekat yang betul-betul dipercaya Soeharto. Sebab, jika orang itu mulai
menonjol dan dianggapnya “keluar” dari arahannya, ia akan digencet.
Elson menganggap Soeharto tak akan menghancurkan lawan (pesaingnya)
apabila dia melihat kesempatan untuk membuat sang lawan berubah menjadi
anak buahnya. Bila tak tunduk, ia akan berusaha keras mengisolasi
pesaingnya hingga dia tidak akan mendapat dukungan. Sepanjang sejarah,
kita lihat Ali Sadikin yang “dibuang” di masa Orde Baru. Bahkan soal
sepele seperti bentuk mata uang pun bisa jadi masalah besar bagi
Soeharto.
Ketika Jusuf Ronodipuro mengusulkan agar
kita memiliki uang kertas bergambar Sukarno, Soeharto tak setuju kalau
Soekarno hanya tampil sendirian. Akhirnya, uang pecahan itu diputuskan
menampilkan gambar Sukarno-Hatta. Menurut Elson, unsur pembalasan dendam
juga menjadi bagian gaya kepemimpinan Soeharto. Seorang sumber TEMPO
menceritakan, begitu Sultan Hamengku Buwono IX menjadi wakil presiden,
ia ingat betapa Soeharto tampak senang. Kepada sumber TEMPO tersebut,
Soeharto mengatakan bahwa kini Raja Jawa-lah yang harus tunduk pada
dirinya-petani dari Desa Kemusuk. Dari pernyataan itu, terasa udara
dendam kelas.
Kelemahan utama dalam kepemimpinan
Soeharto adalah dia bukan pemimpin yang memiliki visi. Model
kepemimpinannya, menurut Elson, sangat instrumental, sederhana.
Langkah-langkah yang diambilnya banyak yang karena kebutuhan konkret dan
praktis. Ia seolah pengamal ekstrem pepatah Latin, Carpe Diem: raihlah
hari ini. Soeharto tak banyak membaca. Elson pernah mendapat cerita
bagaimana seorang lingkaran dalam Istana pernah diam-diam ingin
“mendidik” Soeharto.
Setiap pekan, sang sumber ini membawa
setumpuk majalah luar negeri, seperti Time, ke ruang kerja Soeharto.
Tapi, tiap kali ia datang, tumpukan majalah itu tak tersentuh. Sekali
waktu di Yogyakarta, Sukarno menyebut Soeharto sebagai koppig (keras
kepala). Sikap koppig ini juga terasa bagi masyarakat di bawah
pemerintahannya karena Soeharto begitu defensif apabila ditanya soal
bisnis keluarganya. Bahkan, ketika tahun 1990-an model nepotisme yang
dia bangun rentan terhadap krisis, ia tetap defensif. Soeharto, menurut
Elson, sedari awal selalu membutuhkan sumber-sumber pemasukan off budget
(di luar pembukuan) yang tidak melalui pemeriksaan ketat. Ia
menciptakan mesin-mesin uang seperti Ibnu Sutowo, yang sepak terjangnya
di luar anggaran. Pada waktu itu, semua berjalan lancar karena faktor
boom minyak. Semua “pelanggaran” yang dilakukan seolah terlegitimasi
dengan kesuksesan Pertamina membangun apa saja. Penempatan personel
militer ke dalam lapisan elite perusahaan sipil juga seolah menjadi
absah.
Tahun 1967, ia menempatkan Soejono
Humardani sebagai dewan utama Bank Windu Kencana milik Liem Sioe Liong.
Ia seolah memberi model bagaimana tentara harus memanfaatkan
sumber-sumber bisnis untuk membiayai operasinya. Ia juga membiarkan
ketika istrinya, Tien Soeharto, mendirikan yayasan-yayasan filantropis
yang dananya diperoleh dari perusahaan-perusahaan. Tahun 1966, bersama
istri Ibnu Sutowo, Tien Soeharto mendirikan Yayasan Harapan Kita, yang
dananya dijatah beberapa persen dari PT Bogasari.
Selanjutnya, lingkup yayasannya tambah
beragam, dari yayasan agama sampai yang bersifat tradisi seperti Yayasan
Mangadek, sebuah yayasan untuk memelihara Istana Mangkunegaran yang
pasokan dananya dikoordinasi pengusaha Sukamdani. Soeharto, mengutip
istilah Harry Tjan Silalahi, adalah seorang pemimpin petani yang
memiliki mentalitas lumbung. Seorang petani sehari-hari penampilannya
sederhana, cukup mengenakan kaus, asal lumbungnya penuh. Sosok Soeharto
terlihat sederhana, tak suka pesta-pesta. Tapi ia puas lumbung
keluarganya, sanak familinya, kroninya terisi untuk tujuh turunan.
Mengutip analisis Jenderal Soemitro, Elson menyebut Soeharto memang
lemah terhadap keluarganya. Itulah sebabnya kondisi fisiknya semakin
merosot setelah kematian istrinya pada 28 April 1996. Padahal,
sebelumnya saat kunjungan ke Kazakhstan, kondisi fisiknya masih bagus.
Ia dikabarkan masih kuat menunggang kuda lokal yang larinya cepat.
Sayang, Elson tak menjelajahi soal kematian Tien Soeharto.
Benarkah isu-isu yang tersebar selama
ini? Atau ada fakta lain? Tentunya itu menarik diulas. “Kematian Ibu
Tien karena serangan jantung seperti yang ditulis Elson itu tidak
benar,” kata Muhono, yang di hari-hari kematian Tien Soeharto mengetahui
keadaan dan suasana Cendana. Buku ini memang banyak bertumpu pada
banyak pustaka dan riset dalam rangka upaya Elson mencari atau
me-nemukan gaya personal kepemimpinan Soeharto. Inilah sebuah gaya yang,
celakanya, begitu tertanam dalam birokrasi modern Indonesia. Elson
tidak melakukan wawancara dengan Soeharto. Tapi, itu bukan soal. Sebab,
Cyndi Adams, yang menyusun biografi Sukarno berdasar wawancara yang
dalam dengan “pujaan”-nya itu, malah membuat bukunya itu mengandung
banyak bias emosional.
Buku Elson terbilang cukup komprehensif
hanya bila pembaca ingin mengetahui garis besar perjalanan politik
Soeharto. Tapi, bila pembaca membaca buku ini dengan semangat
“pembongkaran” sesuatu yang baru dalam misteri sosok Soeharto, atau jika
ingin mendapat informasi atau data tekstual yang mengejutkan, tampaknya
buku ini tak bisa menjadi pilihan.
Sebagaimana fitrah profesi penulisnya,
buku ini adalah sebuah analisis yang komprehensif tentang petualangan
politik Soeharto yang disusun dengan rapi dan teliti tanpa gelora atau
keinginan untuk menggebrak.
*Sumber: Arsip Majalah Tempo
Sejarah.